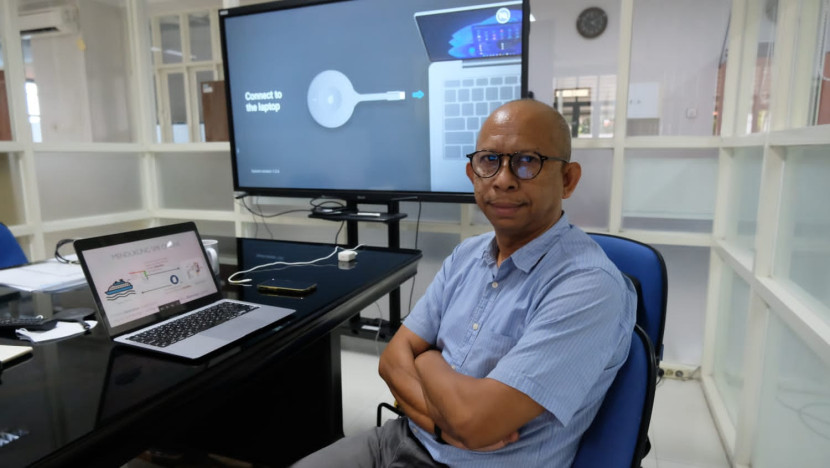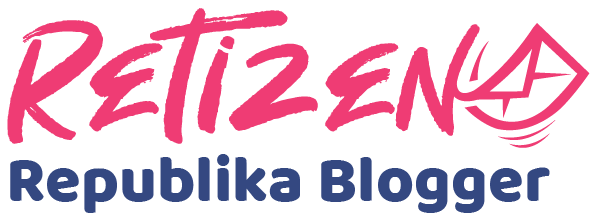Rizki Mubarok
Rizki Mubarok
Bayang-Bayang Hilirisasi Energi Terhadap Penambangan Nikel di Raja Ampat
Humaniora | 2025-06-07 08:13:43
Pada tahun 2023, Kepulauan Raja Ampat resmi diakui sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp). Pengakuan ini menegaskan status Raja Ampat sebagai salah satu kawasan laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Terletak dalam kawasan Segitiga Terumbu Karang atau Coral Triangle yang meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste, wilayah ini menjadi rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan, 700 spesies moluska, dan 537 spesies karang yang mewakili sekitar 75% spesies karang dunia. Selain keanekaragaman hayatinya, Raja Ampat juga menyimpan warisan geologi dan budaya yang terbentuk sejak era Silur-Devon atau sekitar 400 juta tahun yang lalu, dengan lanskap karst unik dan situs arkeologi berupa lukisan gua prasejarah.
Sehingga, Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 435/2009 menetapkan kawasan Raja Ampat sebagai wilayah ekowisata dan konservasi perairan nasional. Tak hanya pemerintah, masyarakat adat di Raja Ampat juga turut berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui sistem kearifan lokal seperti sasi, yaitu praktik pelarangan sementara atas pemanfaatan sumber daya tertentu guna menjaga keseimbangan ekosistem. Integrasi antara sistem adat dan konservasi modern terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya laut hingga 40%, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat lokal.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul kekhawatiran atas dampak ekspansi industri pertambangan nikel terhadap keberlanjutan ekosistem Raja Ampat. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa aktivitas penambangan telah kembali berlangsung setelah pencabutan moratorium pada tahun 2017. Pulau Gag, yang tergolong sebagai pulau kecil dengan luas sekitar 56 km², menjadi salah satu lokasi utama kegiatan penambangan nikel.
Di sisi lain, nikel merupakan komoditas strategis dalam mendukung transisi energi bersih, terutama untuk produksi baterai kendaraan listrik. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah menempatkan hilirisasi mineral sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020–2024. Namun, dinamika ini menimbulkan tantangan tersendiri ketika kegiatan ekstraksi sumber daya dilakukan di kawasan yang sensitif secara ekologis.
Beberapa kajian menunjukkan bahwa penambangan di wilayah seperti Pulau Gag dapat berdampak terhadap tutupan hutan, kualitas tanah, serta habitat spesies endemik. Proses pengerukan tanah juga berpotensi menghasilkan sedimentasi yang memengaruhi ekosistem terumbu karang di sekitar area tambang. Di sisi lain, lalu lintas kapal pengangkut nikel meningkatkan risiko pencemaran laut. Dampak-dampak ini menjadi perhatian karena dapat memengaruhi sektor perikanan dan ekowisata, yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat.
Secara regulatif, aktivitas pertambangan di kawasan seperti Raja Ampat perlu merujuk pada berbagai undang-undang, seperti UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penyederhanaan proses perizinan melalui UU Cipta Kerja 11/2020 membawa implikasi tersendiri, termasuk dalam aspek transparansi dan Kegiatan pertambangan di Raja Ampat saat ini melibatkan beberapa perusahaan dengan konsesi yang cukup luas.
Misalnya, PT Gag Nikel yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya Generasi V dan memiliki konsesi seluas 13.136 hektare di Pulau Gag. Selain itu, aktivitas pertambangan juga terjadi di Pulau Kawei melalui PT Kawei Sejahtera Mining, dengan luas konsesi mencapai 5.922 hektare. Luas konsesi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan dampak kumulatif terhadap ekosistem pulau kecil dan kawasan perairan di sekitarnya. Dalam konteks ini, evaluasi komprehensif terhadap dampak lingkungan, sosial, dan hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan kawasan konservasi.
Dari sisi pemerintah daerah, Dinas Pertambangan Papua Barat (2024) misalnya mengungkapkan pajak dari PT Kawei Sejahtera Mining menyumbang 120 miliar pertahun. Artinya sektor pertambangan dipandang sebagai salah satu potensi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi. Namun demikian, pertimbangan ekonomi tersebut perlu diseimbangkan dengan pengelolaan risiko ekologis dan sosial yang mungkin timbul, terutama dalam jangka panjang.
Peningkatan permintaan global terhadap nikel, sebagaimana dicatat oleh International Energy Agency (2023) yang menyebutkan lonjakan hingga 300% dalam lima tahun terakhir telah memicu percepatan eksplorasi dan produksi nikel di berbagai wilayah, termasuk Raja Ampat. Hal ini menimbulkan paradoks antara percepatan transisi energi dan upaya menjaga ekosistem yang menjadi bagian dari solusi iklim itu sendiri.
Konflik sosial di lapangan pun tidak terhindarkan. Masyarakat adat yang selama ini mempraktikkan pengelolaan wilayah secara lestari menghadapi tantangan baru ketika ruang hidup mereka bersinggungan dengan aktivitas industri. Ketidakseimbangan ini menimbulkan risiko marginalisasi serta tergerusnya sistem sosial-ekologis yang telah berjalan secara turun-temurun.
Melihat hal tersebut, beberapa pakar menjawab tantangan dengan mengusulkan langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Moratorium Izin Tambang Baru
Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap penerbitan izin baru di kawasan sensitif seperti Raja Ampat, termasuk kajian AMDAL yang mempertimbangkan dampak kumulatif lintas sektor.
2. Penguatan Ekonomi Biru Berbasis Masyarakat
Pengembangan alternatif seperti ekowisata partisipatif, konservasi berbasis komunitas, dan kredit karbon biru berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.
3. Reformasi Kebijakan dan Pemantauan
Penyesuaian regulasi agar lebih responsif terhadap perlindungan kawasan konservasi dan hak masyarakat lokal. Pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis satelit dan drone bawah air juga perlu ditingkatkan guna memastikan akuntabilitas.
Melindungi Raja Ampat dari kerusakan yang tidak dapat dipulihkan bukan hanya soal menjaga lanskap alam, melainkan juga memastikan bahwa transisi menuju energi bersih tidak mengorbankan ekosistem penting dan masyarakat yang bergantung padanya. Kolaborasi lintas pihak seperti pemerintah, masyarakat adat, ilmuwan, pelaku usaha, dan komunitas internasional, menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Masa depan kawasan Raja Ampat akan sangat bergantung pada keberanian mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan kebutuhan hari ini, tetapi juga demi generasi mendatang.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.